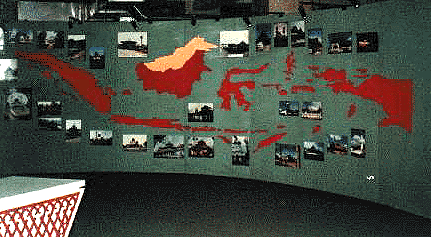
Itu semua yang patut diketahui, tepatnya dan perlunya. Bila ada yang mengatakan tidak perlu tahu, itulah yang tidak akan setia kepada keahlian dirinya; mengabaikan ajaran leluhur kita, pasti ditunggu oleh neraka; bila keahlian tidak dimanfaatkan, bila kewajiban tidak dipenuhi untuk mencapai kebajikan dan kesejahteraan, karena semua itu ketentuan dari hyang dan dewata.
1.
Tulisan ini mencoba untuk mengangkat suatu sisi yang jarang sekali disentuh dalam pembahasan-pembahasan mengenai arsitektur Sunda. Sisi itu adalah kajian naskah, terutama naskah-naskah lama yang meskipun tidak terdapat dalam jumlah banyak namun sangat berguna untuk menguak kehidupan berbudaya pada masa ditulisnya. Sangat beruntung pula bahwa sifat naskah-naskah Sunda lama banyak yang berupa gambaran kehidupan masyarakat yang cukup rinci. Beberapa contoh yang sedang atau telah dialih-aksara dan alih-bahasakan, bahkan ada yang dilengkapi dengan kajian kritis dari pakar-pakarnya; antara lain naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian, Amanat dari Galunggung, Carita Parahyangan dan Perjalanan Bujangga Manik.
Sesuatu yang juga menarik dalam naskah-naskah lama Sunda adalah kenyataan bahwa naskah-naskah itu dapat dipastikan waktu penulisannya. Hal ini sangat mempermudah kita untuk mendudukkan naskah tersebut dalam kerangka sejarah umumnya. Dengan demikian berarti bahwa kita punya bandingan lain mengenai situasi politik, pengaruh-pengaruh aliran kebudayaan luar, dan dinamika kemasyarakatannya; berdasarkan perbandingan data ini kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dapat lebih dipertanggung-jawabkan. Meskipun di sisi lain harus diakui bahwa sejarah masa klasik Jawa Barat masih penuh dengan simpang-siur data dan banyak pertentangan pendapat.
Dalam perbincangan-perbincangan mengenai arsitektur Sunda, sampai sekarang kita masih terpaku pada masalah-masalah peri-bentukan (morfologis) arsitektural saja. Bukan berarti bahwa masalah tadi tidak penting, tetapi kenyataan bahwa sampai sekarangpun masyarakat Sunda dalam membina lingkungannya cenderung menitik-beratkan sisi-sisi ekologis seharusnya dapat menyadarkan kita lebih awal bahwa arsitektur Sunda memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar bentuk atap. Mungkin ada kelompok budaya yang aspek bentukannya sedemikian menonjol sehingga melalui satu aspek saja sudah cukup untuk 'berteriak'. Arsitektur di Tatar Sunda nampaknya lebih condong untuk integratif, paduan dari banyak unsurnyalah yang akan menampilkan jati-dirinya, bukan hanya dari satu unsur saja. Kalau benar demikian, adalah tugas kita untuk melacak berbagai unsur tersebut meungpeung contoh-contoh aslinya belum terlalu banyak yang lenyap dan data-data bandingnya sudah mulai terkumpul.
2.
Naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian (SSK) aslinya ditulis pada daun nipah dan dalam bahasa serta aksara Sunda kuno. Naskah ini terdaftar sebagai MSB (Manuscript Soenda B) dengan nomor kropak 630 pada Museum Nasional di Jakarta. Oleh pemilik lamanya, R. Saleh, naskah ini diserahkan bersama-sama dengan dua naskah lainnya kepada (waktu itu) Batavia Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Dalam jurnal ilmiahnya (TBG) tahun 1867, K.F. Holle mengulas secara singkat mengenai sumbangan ini dan mengemukakan kekagumannya akan nilai naskah yang selesai ditulis pada bulan 3 tahun 1440 Saka atau sama dengan tahun 1518 Masehi ini.
Namun baru setelah lebih dari satu abad kemudian, yaitu tahun 1973, ada sarjana kita yang membuat alih-aksara (transkripsi)nya, yaitu Drs. Atja. Karya yang masih berbentuk stensilan dan beredar dalam jumlah yang terbatas ini diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran. Edisi berikutnya, yang ditambah dengan pengalih-bahasaan dan penjelasan mengenai istilah-istilah dikerjakan oleh Atja dan Saleh Danasasmita; baru diterbitkan pada tahun 1981 oleh Proyek Pengembangan Museum Jawa Barat. Terbitan yang disebut terakhir inilah yang digunakan untuk menjadi landasan telaah ini. Dengan sendirinya segala manfaat yang mungkin diperoleh hadirin adalah atas jasa kedua tokoh di atas. Kepada merekalah penghormatan dan ucapan terimakasih harus diarahkan, sedangkan semua kejanggalan dan cacat pasti merupakan hasil-karya penulis makalah ini.
3.
Bagian mengenai klasifikasi lahan dapat kita temui dalam lembar XXII, baris 533-537 mengenai tanah larangan, tanah atau lahan yang dianggap sampah bumi atau mala ning lemah. Penulis SSK membawa kita ke dalam masalah klasifikasi tadi sewaktu membicarakan perbuatan-perbuatan manusia yang salah, yaitu catur buta; empat hal yang mengerikan; burangkak, marende, mariris dan wirang. Orang yang semasa hidupnya berkelakuan burangkak, yaitu ketus, tak mau menyapa sesamanya, bicara sambil marah dan membentak, bicara sambil membelalak, bicara kasar dengan nada menghina, buruk kelakuan, berhati panas; diibaratkan sebagai raksaksa, durgi durga, kala, buta pendeknya mahluk-mahluk yang menghuni mala ning lemah. Paling menarik pada bagian ini adalah uraian klasifikasi yang berdasarkan pada feature topologis. Berbeda sekali dengan klasifikasi lahan yang banyak dipergunakan sejak akhir abad lalu dalam Paririmbon yang lebih mengandalkan konsep abstrak Mandhala! dari Silpa Sastra dan nampaknya diterima melalui kraton Mataram.
Untuk klasifikasi lahan yang dinamakan nirmala ning lemah dapat ditemui dalam lembar XXIV dan XXV baris 594-596. Orang-orang yang ingat kepada sanghyang siksa, berpegang teguh kepada ajaran mereka yang lebih tua, mengetahui peraturan, mengukuhkan kata-kata sentosa; mereka dikatakan muncul dari kesucian tanah atau nirmala ning lemah. Namun nirmala ning lemah jelas berupa nama-nama tempat (bangunan) pemujaan, tempat-tempat yang bermakna religius. Oleh karena itu tidak dapat kita masukkan dalam pembahasan klasifikasi lahan. Bagian ini lebih sesuai untuk dibicarakan pada kesempatan lain, pembicaraan mengenai tipologi bangunan. Jadi waktu ini pembahasan kita batasi hanya pada bagian mengenai mala ning lemah.
Di bawah ini terdapat daftar mala ning lemah berikut terjemahan yang diberikan oleh Atja dan Saleh Danasasmita. Pada baris berikutnya, setelah tanda (+), ditambahkan keterangan lebih lanjut yang diperoleh dari hasil wawancara dengan seorang budayawan dari Indramayu dan beberapa kamus bahasa Sunda. Keterangan-keterangan dari kamus terutama diperoleh dari A Dictionary of the Sunda Language of Java (J. Rigg/ 1862), Soendaneesch Hollandsch Woordenboek (A. Geerdink/1875) dan Soendaneesch-Hollandsch Woordenboek (S. Coolsma/1943).
Lembar XXII: baris 533 sampai dengan 537,
Terjemahannya : Yang disebut kotoran bumi ialah:
4.
SSK menyatakan bahwa semua itu adalah keletakan-keletakan yang tidak layak dihuni manusia. Pengertian huni ini tidak jelas, apakah hunian itu untuk satu keluarga batih seperti sekarang (=rumah) ataukah hunian kolektif seperti kampung atau babakan. Rupanya penulis SSK beranggapan bahwa hal ini sudah jelas bagi para pembacanya saat itu, sehingga tidak merasa perlu untuk diperjelas lagi.
Pada masa itu (awal abad XVI) dapat kita perkirakan bahwa masyarakat Sunda kebanyakan, yaitu mereka yang berdiam diluar dayeuh atau kraton sudah mulai diresapi kebudayaan India walaupun tidak pernah seintensif seperti yang terjadi di Majapahit atau Bali. Dari bandingan yang dapat kita peroleh dari pemukiman-pemukiman di Kampung Naga/ Tasikmalaya, Kampung Dukuh/ Cikelet, Kampung Pulo/ Leles yang didirikan sekitar awal abad XVII (jadi kira-kira satu abad lebih kemudian), masih banyak terlihat pengaruh kebudayaan Megalitik. Menilik bahwa kampung-kampung di atas didirikan oleh tokoh-tokoh yang beragama Islam (kemungkinan sisa-sisa laskar Mataram yang menyerbu Batavia tahun 1628-29) tetapi tata letak kampungnya tetap memperlihatkan ciri-ciri seperti pola perletakan rumah-rumahnya yang mengarah sumbu Timur-Barat, adanya bangunan kolektif menghadap suatu tanah lapang yang digunakan untuk upacara-upacara pemujaan kesuburan, penghormatan kepada bentukan silang di bubungan rumah dan s! eterusnya. Maka dapat dibayangkan bahwa satu abad sebelumnya -ingat bahwa pengaruh kebudayaan India juga hanya di permukaan- suasana kampung di pedalaman Jawa Barat tidak jauh berbeda. Yang terpenting adalah bahwa pada masa itu bagian terbesar masyarakat Sunda sudah hidup menetap dan men gandalkan pertanian sebagai pola hidupnya. Di fihak lain harus diingat pula bahwa masih ada sebagian masyarakat yang masih pada pola hidup berburu dan mengumpulkan makanan seperti yang digambarkan beberapa penulis Barat pada akhir abad lalu. Mereka masih melaporkan adanya kelompok-kelompok masyarakat seperti itu di Priangan Selatan terutama di Banten Selatan.
Masa itu struktur arsitektural kampung sudah baku, bahkan secara visual mungkin tidak bisa kita bedakan dengan kampung-kampung agak ke pedalaman masa ini. Unsur-unsur terpenting kampung adalah (1) rumah adat (bumi ageung) yang kemudian bergeser fungsi menjadi langgar atau mesjid, namun tetap merupakan pusat kegiatan masyarakatnya; (2) rumah keluarga batih, yaitu kediaman sepasang suami isteri dengan anak-anak lelaki yang belum aqil-balik dan anak perempuan yang belum kawin, ditambah beberapa kerabat-darah terdekat; dan (3) bangunan penyimpanan dan pengolahan padi, yaitu leuit dan saung lisung kolektif. Mungkin masih ada bangunan-bangunan lain seperti rumah huma, bangunan penjagaan dan lain-lain tetapi tidak merupakan unsur yang tipikal. Mungkin orientasi bangunan masih menaati sisa-sisa pemujaan kesuburan dengan mengutamakan arahan-arahan Timur-Barat.
Dengan demikian kita anggap bahwa hunian dalam SSK berarti keduanya, bisa sebagai satu satuan pemukiman yang terdiri dari paling tidak 3 tipologi bangunan dan berjumlah antara 15-30 unit; atau bisa juga sebagai satu unit tempat tinggal keluarga batih (rumah) baik masih sebagai one-room basic house maupun sudah dikembangkan menjadi multi-room house.
Sekarang kita coba pilah istilah-istilah di atas agar dapat lebih mudah kita fahami. Untuk mudahnya, kita ambil pembagian berdasarkan makna magico-religiusnya :
A. Lahan 'berisi' unsur magico-religius :
B. Lahan 'kosong', semata-mata formasi topologis :
Kelompok A adalah kelompok yang jelas dihindari, tidak memerlukan keterangan lebih banyak, kita sudah mafhum akan larangan mengganggu lahan-lahan yang ada di bawah 'penilikan' saudara-saudara kita dari alam sebelah itu.
Kelompok B merupakan kumpulan lahan yang tidak terlibat masalah magis dan 'mengerikan' seperti A, jadi seharusnya ada penjelasan lain mengapa tidak boleh dihuni. Tetapi satu kelompok, yaitu (a) dengan segera memperlihatkan hal-hal yang menghalangi pembangunan berjalan mudah dan lancar. Paling tidak diperlukan tenaga, bahan dan waktu jauh lebih besar untuk dapat membangun pada lahan-lahan semacam itu. Pemborosan untuk satu pribadi/ kelompok atas tanggungan banyak pribadi lain dalam suatu masyarakat yang demokratis adalah dosa.
Berlainan dengan kelompok berikutnya, Bb, kelompok ini tidak menuntut pemborosan material, bahkan beberapa, seperti (1), (3), (4), (5), (6), merupakan lahan yang menyediakan beberapa kemudahan seperti bidang-bidang alami yang sudah ada, struktur penyangga lebih kuat, potensi militer, untuk menyebut beberapa. Toh termasuk tanah larangan. Satu-satunya kelemahan kelompok ini adalah bahwa tidak pernah ada formasi seperti itu dalam luasan yang cukup besar untuk menampung satu kompleks pemukiman; atau tidak membuka kemungkinan untuk diperluas dengan mempertahankan kelebihan yang ada. Sedangkan (10) dan (14b) berupa tonjolan pada permukaan, bukit, sehingga sekali lagi tidak mungkin diperoleh dalam luasan yang cukup.
Ada dua kemungkinan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, sebagai masyarakat agraris yang juga demokratis, lahan-lahan sempit semacam itu tidak memungkinkan adanya keadilan dalam pengkaplingannya. Sebagian akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar daripada sebagian besar kelompoknya. Dengan sendirinya iklim semacam ini mudah sekali menjadi pangkal pertikaian yang sangat dihindari oleh masyarakat agaris. Para tetua yang bijaksana lalu memutuskan untuk melarang penggunaan lahan-lahan semacam ini, bibit kecemburuan sosial saja nanti jadinya.
Kalau kita tilik dari sudut pandang masyarakat dengan pola hidup berburu dan mengumpulkan makanan, segera kita sadari bahwa kelompok Bb adalah lahan-lahan yang 'ideal' bagi mereka. Sebagai lahan untuk kediaman sementara, dengan teknologi sederhana, keletakan-keletakan itu menyediakan kemudahan-kemudahan yang nyata. Apalagi kelompok berburu dan pengumpul makanan (forager) ini jarang melebihi bilang belas dalam jumlahnya, justru demi mobilitas kelompok itu sendiri. Kemudian keletakan-keletakan itu juga menjanjikan kemudahan militer, dalam arti mudah untuk dipertahankan atau berupa tempat yang tinggi sehingga bahaya sudah dapat diketahui jauh sebelum sampai. Maklum bentrokan antar kelompok yang saling melanggar teritorial tidak resmi mereka pasti sering terjadi.
Tetapi zaman berubah, kelompok pengolah tanah semakin besar jumlahnya dan dalam struktur kenegaraan formal, pola kehidupan menetap adalah pola yang 'direstui' atasan. Sampai sekarangpun pemerintah selalu berusaha untuk memukimkan suku-suku terasing dan mencurigai pola hidup yang berpindah-pindah. Dalam pergeseran budaya ini dengan sendirinya salah satu fihak akan menjadi terkucil, oleh kelompok yang dominan pola kehidupan yang baru ditinggalkan tetapi masih dianut sementara saudara mereka itu dipandang lebih rendah, sesuatu yang harus dihindari dan disingkiri. Pandangan ini dibakukan menjadi tabu bagi masyarakat yang dominan.
5.
Akhirul kalam, walaupun keinginan untuk membahas lebih jauh masih menggoda, apa daya kemampuan hanya sampai di sini, terpaksa pembahasan dihentikan. Sebelum benar-benar tammat, ada beberapa butir yang dapat kita simpulkan dari bahasan sederhana di atas.
Bandung, 22 Oktober 1989.
Return to SASAKALA
Return to LSAI Home Page